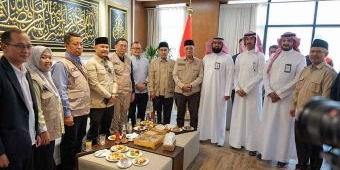Khariri Makmun. Foto: bangsaonline
Khariri Makmun. Foto: bangsaonline
Oleh: Khariri Makmun
Ada momen langka dalam sejarah diplomasi global ketika sebuah negara tiba-tiba naik kelas, bukan karena ambisi agresif, tapi karena kepercayaan yang ditaruh kepadanya. Itulah yang sekarang dialami Indonesia. Iran secara terbuka meminta Indonesia ikut menetralkan propaganda Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pada saat yang sama, Indonesia menandatangani mega-deal Rp437 triliun dengan Arab Saudi. Dunia pun bertanya: apakah Indonesia sedang dipersiapkan menjadi “game changer” baru dalam percaturan Timur Tengah?
Tanggal 2 Juli 2025 bisa jadi akan dikenang sebagai tonggak baru diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), menghasilkan kesepakatan investasi raksasa. Dari energi hijau, bahan bakar penerbangan, hingga layanan kesehatan untuk haji dan umrah, semuanya dikunci melalui pembentukan “Supreme Coordination Council”, sebuah Dewan Tinggi Bilateral yang levelnya setara kemitraan strategis utama.
Di tengah guncangan geopolitik global — Iran yang terhimpit sanksi, Israel makin agresif, dan Barat terus memperketat narasi — Indonesia tiba-tiba muncul sebagai opsi alternatif: netral tapi vokal, demokratis tapi bernapas Islam. Sebuah posisi yang jarang dimiliki negara lain.
Kenapa Iran tiba-tiba menyebut Indonesia sebagai aktor penting? Jawabannya sederhana: perang hari ini tidak lagi semata-mata ditentukan di medan tempur, tapi juga di arena opini publik. Menurut pengamat geopolitik Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, Indonesia punya dua modal yang tidak bisa diremehkan: legitimasi moral sebagai negara muslim terbesar di dunia, dan kredibilitas sebagai demokrasi. Kombinasi ini unik, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Iran, Arab Saudi, apalagi Mesir yang sering terjebak pada kepentingan internal dan rezim politik otoriter.
Iran sadar betul bahwa narasi mereka tentang Palestina atau perlawanan terhadap Israel kerap dianggap bias. Selama ini, suara Iran diidentikkan dengan kepentingan ideologis dan persaingan sektarian di kawasan. Tapi lain ceritanya jika Indonesia yang bicara. Dunia lebih mau mendengar, bahkan pihak Barat sekalipun cenderung menanggapi dengan tenang. Di sinilah yang disebut oleh Lina Khatib dari Chatham House sebagai "moral leverage" Indonesia—kekuatan moral yang melampaui kekuatan militer.
Indonesia tidak datang dengan retorika perang atau kepentingan blok tertentu. Indonesia membawa suara mayoritas umat Islam dunia yang hidup dalam kerangka demokrasi, pluralisme, dan konsensus. Ketika Jakarta bersuara, ia tidak mewakili satu mazhab atau sekte, tapi mewakili keragaman. Itulah yang membuat posisi Indonesia unik: mampu bicara dengan semua pihak tanpa menimbulkan kecurigaan berlebihan.
Lebih jauh lagi, ketika propaganda Barat mengunci Iran lewat framing media global, Indonesia punya ruang untuk hadir sebagai jembatan. Netralitas aktif Indonesia bukan sekadar jargon era Soekarno yang lahir di Bandung 1955, melainkan sebuah strategi yang relevan lagi hari ini. Dunia multipolar yang penuh dengan rivalitas blok justru membutuhkan aktor semacam Indonesia, yang tidak punya kepentingan ekspansionis tapi punya kepentingan besar terhadap stabilitas global.
Dengan demikian, permintaan Iran agar Indonesia ikut dalam “perang opini” melawan propaganda Barat bukan hal aneh. Itu logis. Justru ini menegaskan bahwa Indonesia sedang memasuki level baru dalam diplomasi global. Pertanyaannya kini: apakah Indonesia siap mengelola “moral leverage” ini menjadi kekuatan strategis nyata? Atau sekadar berhenti di simbol tanpa arah yang jelas?
Deal Rp437 Triliun dengan Arab Saudi
Mega-deal Indonesia dengan Saudi jelas bukan sekadar hitungan uang. Nilainya memang fantastis—Rp437 triliun—tapi dampaknya jauh lebih dalam. Menurut analis ekonomi energi dari ISEAS Singapura, Nurliana Darsono, langkah Saudi ini adalah strategi pergeseran orientasi. Mereka tidak bisa selamanya bergantung pada minyak mentah, sementara "Saudi Vision 2030" menuntut diversifikasi besar-besaran. Untuk itu, Riyadh butuh mitra muslim besar yang demokratis, punya legitimasi global, dan relatif stabil. Indonesia masuk sebagai kandidat ideal: pasar besar, demokrasi yang berjalan, dan citra internasional yang kuat.
Arab Saudi dengan kesepakatan ini juga ingin mengirimkan sinyal geopolitik. Mereka tidak lagi sekadar menatap ke Barat, melainkan merangkul Asia dengan lebih serius. Indonesia muncul sebagai pintu masuk strategis, bukan hanya karena jumlah penduduk muslimnya, tapi juga karena statusnya sebagai kekuatan menengah yang dipercaya dunia. Dalam konteks ini, kesepakatan Indonesia-Saudi bukan hanya kerja sama ekonomi, melainkan juga pesan politik: Riyadh siap bermain di panggung multipolar dengan mitra-mitra baru.
Ekonom senior dari INDEF, Bhima Yudhistira, menekankan dimensi lain dari kesepakatan ini. Ia menyebutnya sebagai “modal diplomasi ekonomi” yang jarang dimiliki Indonesia. Menurutnya, investasi sebesar itu jangan dilihat sekadar sebagai angka, tapi sebagai leverage politik global. Jika dikelola dengan benar, deal ini bisa mengubah posisi Indonesia dari sekadar penerima investasi menjadi pemain yang punya daya tawar. Artinya, modal ekonomi bisa diterjemahkan menjadi modal diplomasi, sesuatu yang amat penting di era kompetisi geopolitik saat ini.
Lebih dari itu, mega-deal ini memperlihatkan peluang Indonesia untuk keluar dari jebakan hubungan yang timpang. Selama ini, kerjasama dengan negara besar kerap menempatkan Indonesia sebagai pihak yang pasif. Kali ini berbeda: ada ruang untuk membangun relasi lebih setara. Saudi membutuhkan Indonesia sama besarnya dengan Indonesia membutuhkan Saudi. Itu artinya, bargaining position Indonesia meningkat, asal tidak disia-siakan dengan manajemen yang lemah atau kebijakan yang plin-plan.
Dengan kata lain, kesepakatan Rp437 triliun ini adalah momentum. Momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar, bukan hanya “penerima” modal, tapi juga penggerak yang mampu mengarahkan kerjasama pada visi strategis jangka panjang. Pertanyaannya sekarang: apakah Indonesia bisa mengubah peluang ini menjadi pijakan baru dalam percaturan global? Atau akan berhenti di seremoni angka besar tanpa efek nyata bagi kepentingan bangsa?
Simbolisme Politik Global
Di titik ini, dunia mulai membaca tanda-tanda arah baru politik luar negeri Indonesia. Iran menggandeng Jakarta untuk perang narasi melawan hegemoni Barat dan Israel, sementara Arab Saudi membuka pintu kemitraan strategis melalui mega-investasi Rp437 triliun. Dua kekuatan besar Timur Tengah yang biasanya saling berseberangan justru sama-sama menaruh harapan pada Indonesia. Ini bukan sekadar kebetulan, tapi sinyal kuat bahwa Jakarta dipandang punya posisi unik: netral, demokratis, dan bernafas Islam.
Frederic Wehrey dari Carnegie Endowment menilai, “Indonesia bisa jadi satu-satunya aktor yang diterima kedua kubu: blok pro-Iran dan blok pro-Saudi. Itu posisi langka.” Analisis ini masuk akal, karena biasanya negara yang terlalu dekat dengan Iran akan ditolak Saudi, begitu pula sebaliknya. Indonesia justru hadir dengan wajah moderasi: tidak punya kepentingan militer di Timur Tengah, tapi punya legitimasi moral sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Inilah yang membuat Jakarta bisa melampaui sekadar “jembatan,” menuju peran sebagai “broker” perdamaian yang credible.
Bagi Iran, kehadiran Indonesia bisa membantu menembus blokade narasi yang mereka hadapi dari Barat. Bagi Saudi, investasi besar-besaran ke Indonesia bukan hanya urusan bisnis, tapi juga pesan geopolitik bahwa mereka siap merangkul mitra Muslim non-Barat untuk menopang visi transisi global. Dengan kata lain, dua kutub yang berseberangan menemukan relevansi yang sama: Jakarta. Dan ini menandai babak baru politik luar negeri Indonesia yang lebih berani, lebih strategis, dan lebih vokal.
Di dalam negeri, simbolisme ini juga besar. Prabowo Subianto, yang dulu sering dilekatkan dengan citra nasionalis-militeristik, kini justru tampil sebagai figur yang mendorong diplomasi Islam moderat di panggung global. Perubahan ini tidak hanya memperluas wajah diplomasi Indonesia, tapi juga mengirim pesan bahwa kekuatan militer bisa berdampingan dengan soft power diplomasi. Perpaduan inilah yang menjadikan Indonesia semakin diperhitungkan: punya hard power, tapi juga bisa memimpin dengan moral power.
Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa menjadi pemain penting, tapi sejauh mana Jakarta berani memainkan peran barunya. Dunia sedang mencari mediator yang credible, dan Indonesia punya semua modal: populasi Muslim terbesar, demokrasi yang relatif stabil, ekonomi yang tumbuh, serta tradisi politik luar negeri bebas aktif. Jika momentum ini dikelola dengan visi panjang, Indonesia bisa bertransformasi dari sekadar penonton menjadi aktor utama di panggung Timur Tengah — bahkan mungkin global.
Tentu, tidak ada jalan mulus tanpa batu. Indonesia memang dipuji sebagai calon kunci perdamaian, tapi realitasnya jauh lebih rumit. Politik Timur Tengah penuh dengan jebakan. Iran bisa berubah keras kapan saja. Saudi bisa berbalik arah kalau kepentingannya terganggu.
Pengamat geopolitik internasional, Vali Nasr, mengingatkan: “Siapa pun yang ingin jadi mediator di Timur Tengah harus siap menanggung risiko reputasi. Kalau gagal, kredibilitas bisa runtuh.”
Artinya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam euforia. Diplomasi ini harus dijalankan dengan kesabaran, perhitungan matang, dan strategi jangka panjang.
Dari kacamata ekonomi global, Indonesia juga punya peluang emas. Energi hijau, yang jadi salah satu fokus deal dengan Saudi, bisa membuat Indonesia masuk ke "supply chain" global baru. Dunia sedang transisi dari minyak ke energi bersih. Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar, bisa jadi pusat "green energy".
Menurut Nouriel Roubini, ekonom dunia yang sering dijuluki “Dr. Doom”, “negara yang bisa memainkan transisi energi akan punya posisi geopolitik baru.” Dan Indonesia sudah mengunci jalannya dengan Saudi.
Ditambah, sektor layanan haji-umrah bernilai miliaran dolar tiap tahun. Kerjasama kesehatan dan logistik yang ditandatangani akan memperkuat soft power Indonesia di mata umat Islam.
Penutup
Dunia sedang masuk ke gelanggang multipolar, arena tinju raksasa di mana Amerika tidak lagi bisa berdiri sendirian di tengah ring. Cina datang dengan otot ekonomi, Rusia masih menggenggam senjata, sementara Timur Tengah terus melempar percikan api. Di tengah hiruk pikuk itu, ada kursi kosong di tepi panggung—dan dunia menoleh ke Jakarta: apakah kita mau duduk di sana atau sekadar jadi penonton yang bertepuk tangan?
Iran sudah berbisik, Saudi sudah merangkul. Keduanya ibarat dua musuh lama yang sama-sama melirik mediator netral untuk menyeimbangkan meja perundingan. Tapi mediator ini bukan negara adidaya, melainkan Indonesia—sebuah demokrasi muslim terbesar yang punya modal moral sekaligus pasar raksasa.
Pertanyaannya apakah Jakarta berani keluar dari zona nyaman, mengambil risiko, dan melangkah ke panggung besar? Atau kita akan kembali pada pola lama: aman, normatif, tapi steril dari pengaruh global yang nyata?
Sejarah selalu kejam bagi mereka yang ragu. Dunia multipolar tidak menunggu, ia hanya menyambut siapa yang berani berdiri.
Hari ini, sorot lampu sedang mengarah ke Jakarta. Kalau kita menunduk, spotlight itu akan padam. Tapi kalau kita berdiri, inilah momen Indonesia menulis bab baru: dari sekadar penonton, menjadi aktor utama di drama geopolitik global.
Penulis adalah pengamat politik Timur Tengah dan Direktur Moderation Corner, Jakarta.